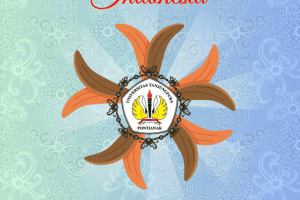Teknologi Diversifikasi Pangan dengan Fortifikasi Tepung Daun dan Biji Kecipir (Psophocarpus Tetragonolobus (L.) DC.) sebagai MP-ASI Solusi Pencegahan Stunting di Kalimantan Barat
Masalah anak pendek (stunting) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang (Unicef, 2013). Stunting merupakan suatu bentuk kegagalan pertumbuhan yang diakibatkan oleh akumulasi ketidakcukupan nutrisi dan berlangsung lama mulai dari kehamilan hingga usia 24 bulan (Hoffman et al., 2000; Bloem et al., 2013). Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat serta terhambatnya pertumbuhan mental (Lewit, 1997; Kusharisupeni, 2002; Unicef, 2013). Dampak stunting pada balita yaitu dapat menurunkan prestasi akademik, meningkatkan risiko obesitas, lebih rentan terhadap penyakit tidak menular dan peningkatan risiko penyakit degeneratif (Hoffman et al., 2000; WHO, 2003; Timaeus, 2012; Crookston et al., 2013; Picauly, 2013; Unicef, 2013). Menurut World Health Organization (2003) sebanyak 54% dari kematian bayi dan balita disebabkan oleh gizi buruk, salah satunya stunting.
Penanganan masalah stunting di dunia selama 20 tahun terakhir sangat lambat. Jika hal tersebut terus berlangsung diprediksi 15 tahun kemudian 450 juta anak-anak akan mengalami keterlambatan pertumbuhan (stunting). Tingginya kasus stunting pada balita dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan ibu, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk serta rendahnya pelayanan kesehatan (Unicef, 1990). Faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus stunting adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi (Unicef, 1990; Hoffman et al., 2000; Umeta, 2003). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2018), provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki prevalensi tinggi dengan kasus stunting pada balita sebesar 30%.
 Upaya yang dilakukan pemerintah Kalimantan Barat dalam mengatasi stunting selama ini hanya melakukan peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi lingkungan (Rahino, 2018). Cara tersebut dinilai masih belum efektif karena stunting terjadi akibat kurangnya asupan makanan bergizi seimbang sehingga kebutuhan asupan makanan dapat menjadi solusi untuk mengatasinya. Pemenuhan zat gizi baik gizi makro maupun gizi mikro sangat dibutuhkan untuk menghindari atau memperkecil risiko stunting. Kualitas dan kuantitas MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang baik merupakan salah satu komponen terpenting dalam makanan karena mengandung sumber gizi makro dan mikro yang berperan dalam pertumbuhan linier (Taufiqurrahman et al., 2009). Pemberian makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, kalsium, vitamin A dan zinc dapat memacu tinggi anak (Kusharisupeni, 2002).
MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI (Winarno, 1987). World Health Organization menerapkan standar MP-ASI untuk bayi harus mengandung protein, energi dan nutrisi yang cukup. Makanan tambahan diberikan untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan nutrisi total pada anak dengan jumlah yang didapatkan dari ASI sekaligus menanamkan kebiasaan makan yang baik (WHO, 2003; Utami, 2011). Pemberian MP-ASI yang cukup kualitas dan kuantitasnya penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang sangat pesat pada periode ini, tetapi sangat diperlukan hygiene dalam pemberian MP-ASI tersebut. Sanitasi dan hygiene MP-ASI yang rendah menyebabkan terjadinya kontaminasi mikroba yang dapat meningkatkan risiko atau infeksi lain pada bayi (Winarno, 1987).
Upaya yang dilakukan pemerintah Kalimantan Barat dalam mengatasi stunting selama ini hanya melakukan peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi lingkungan (Rahino, 2018). Cara tersebut dinilai masih belum efektif karena stunting terjadi akibat kurangnya asupan makanan bergizi seimbang sehingga kebutuhan asupan makanan dapat menjadi solusi untuk mengatasinya. Pemenuhan zat gizi baik gizi makro maupun gizi mikro sangat dibutuhkan untuk menghindari atau memperkecil risiko stunting. Kualitas dan kuantitas MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang baik merupakan salah satu komponen terpenting dalam makanan karena mengandung sumber gizi makro dan mikro yang berperan dalam pertumbuhan linier (Taufiqurrahman et al., 2009). Pemberian makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, kalsium, vitamin A dan zinc dapat memacu tinggi anak (Kusharisupeni, 2002).
MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI (Winarno, 1987). World Health Organization menerapkan standar MP-ASI untuk bayi harus mengandung protein, energi dan nutrisi yang cukup. Makanan tambahan diberikan untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan nutrisi total pada anak dengan jumlah yang didapatkan dari ASI sekaligus menanamkan kebiasaan makan yang baik (WHO, 2003; Utami, 2011). Pemberian MP-ASI yang cukup kualitas dan kuantitasnya penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang sangat pesat pada periode ini, tetapi sangat diperlukan hygiene dalam pemberian MP-ASI tersebut. Sanitasi dan hygiene MP-ASI yang rendah menyebabkan terjadinya kontaminasi mikroba yang dapat meningkatkan risiko atau infeksi lain pada bayi (Winarno, 1987).

(Sumber: Board on Science and Technology for International Development, 1981)
Pembuatan tepung daun kecipir mengacu pada penelitian Zakaria et al. (2012) dilakukan dengan cara daun kecipir dicuci dengan air bersih lalu dirunut dari tangkai daunnya. Kemudian daun kecipir tersebut ditebar di atas jaring kawat (rak jemuran oven) dan diatur ketebalannya sedemikian rupa. Selanjutnya, daun kecipir tersebut dikeringkan dalam oven dengan suhu kurang lebih 450 C selama kurang lebih 24 jam (sudah cukup kering). Pembuatan tepung dari daun kecipir kering menggunakan blender kering dan diayak dengan ayakan 100 mesh untuk memisahkan batang-batang kecil yang tidak bisa hancur dengan blender yang selanjutnya disimpan dalam wadah plastik yang kedap udara.
Teknologi diversifikasi makanan dalam bentuk MP-ASI yang dibuat dari kecipir ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan program pemerintah Kalimantan Barat dalam mengatasi stunting yang selama ini hanya melakukan peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi lingkungan (Rahino, 2018). Keunggulan dari strategi pemberian MP-ASI ini memiliki populasi sasaran yang luas, proses produksi pangan dapat melibatkan langsung masyarakat serta bahan bakunya yang dapat diolah dari jenis sumber daya alam yang selama ini dianggap kurang bernilai guna. MP-ASI ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan produk-produk MP-ASI yang sudah beredar dimasyarakat. Contohnya MP-ASI berbahan dasar jagung dan kacang hijau yang masing-masing hanya memiliki kandungan vitamin A sebesar 860 SI/100 gram dan 157 SI/100 gram, kandungan vitamin A pada daun kecipir dapat mencapai 5.240-20.800 SI/100 gram. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kacang hijau yang hanya memiliki kandungan protein sebesar 22%, kandungan protein pada biji kecipir dapat mencapai 39% (Board on Science and Technology for International Development, 1981; Almatsier, 2004; Suarni dan Widowati, 2006; Mustakim, 2012). Kandungan mineral pendukung pada biji dan daun kecipir juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan MP-ASI berbahan dasar jagung dan kacang hijau sehingga menyebabkan kecipir lebih berpotensi untuk dikembangkan menjadi MP-ASI.
Hal ini juga didukung dengan konsumsi vitamin A yang cukup dapat menghindari penyakit infeksi seperti penyakit saluran pernapasan, diare, demam, konsumsi protein dapat menghindari penyakit stunting, anemia, kelemahan fisik, edema, disfungsi vaskular dan gangguan imunitas serta kekurangan mineral yang dapat menyebabkan rasa letih, mudah flu dan mudah depresi (Almatsier, 2004; Plantenga et al., 2006; Shinya, 2010; Delimaris, 2013; Lee dan Wu, 2015). Ketersedian bahan baku yang melimpah juga tentunya akan menjamin produksi MP-ASI yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan perekonomian petani kecipir. Gagasan mengenai MP-ASI yang kaya vitamin A ini akan terlaksana dengan baik jika mendapat dukungan dari semua pihak khususnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan agar memberikan izin serta bantuan baik materil maupun moril yang langkah kongkretnya dapat berupa pembagian bubur sehat ini kepada balita secara gratis. Perlu pula peran langsung dari Dinas Kesehatan sebagai agen yang menjalankan program kerja kesehatan yang dapat berupa sosialisasi atau memberikan penyuluhan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan sehat serta melakukan pengecekan kondisi asupan gizi balita dan ibu secara rutin setiap bulannya. Dinas Pertanian dan para petani sangat diharapkan peran langsungnya dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman kecipir demi menjamin ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.
Hal terpenting adalah adanya dukungan dari masyarakat untuk membiasakan hidup sehat dengan lingkungan yang bersih, mengonsumsi pangan bergizi serta menjaga kesehatan agar tercapainya Indonesia sehat dan bebas stunting. Teknologi diversifikasi pangan biji dan daun kecipir menjadi tepung dapat meningkatkan kualitas gizi MP-ASI terutama tingginya kandungan vitamin A dan mineral sehingga lebih kaya manfaat. MP-ASI ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis yang murah dan ramah untuk mengatasi stunting karena bahan bakunya yang berasal dari hasil produksi pertanian Kalimantan Barat sendiri. Program kesehatan berupa pangan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual kecipir dan dapat meningkatkan tingkat perekonomian serta taraf hidup petani dan masyarakat di Kalimantan Barat. Selain itu, dengan adanya dukungan dari seluruh pihak dapat mewujudkan terbentuknya masyarakat bebas stunting sekaligus mendukung program Indonesia emas 2045 bebas stunting.
DAFTAR PUSTAKA
Almatsier, S. 2004. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Apriliyanti, T. 2010. Kajian Sifat Fisikokimia dan Sensori Tepung Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatasblackie) dengan Variasi Proses Pengeringan, Skripsi. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
Bloem, M.W., Pee, S.D., Hop, T.L., Khan, N.C., Lailou, A., Minarto, Pfanner, R.M., Soekarjo, D., Soekirman, Solon, J.A., Theary, C., dan Wasantwisut, E. 2013. Key Strategies to Further Reduce Stunting in Southeast Asia: Lessons from the ASEAN Countries Workshop, Food and Nutrition Bulletin. Tokyo: the United Nations University. 34 (2).
Board on Science and Technology for International Development. 1981. Winged Bean, A High-protein Crop for the Tropics. Washington: National Academy Press.
Crookston, B., Penny, M., Alder, S.C., Dickerson, T., Merril, R.M., dan Stanford, J. 2010. Children Who Recover from Early Stunting and Children Who are Not Stunted Demonstrate Similar Levels of Cognition, the Journal of Nutrition. Salt Lake City: University of Utah.
Delimaris, I. 2013. Adverse Effects Associated with Protein Intake above the Recommended Dietary Allowance for Adults, Hindawi Journal. Greece: University of Thessaly.
Dini, L., Tatang, S.F., dan Sunawang. 2007. Program ASI Eksklusif dan MP-ASI, Kumpulan Makalah Diskusi Pakar Gizi tentang ASI, MP-ASI, Antropometri dan BBLR. Cipanas.
Handayani, T. 2013. Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus L.), Potensi Lokal yang Terpinggirkan, IPTEK Tanaman Sayuran. Balai Penelitian Tanaman Sayuran: Kelompok Peneliti Pemuliaan dan Plasma Nutfah.
Hoffman, D.J., Sawaya, A.L., Verreschi, I., Tucker K.L., dan Robert, S.B. 2000. Why are Nutritionally Stunted Children at Increased Risk of Obesity? Studies of Metabolic Rate and Fat Oxidation in Shantytown Children from Sao Paulo, Brazil, the American Journal of Clinical Nutrition. Oxford: Oxford University Press.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 224/Menkes/SK/II/2007 tentang Spesifikasi Teknis Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Kusharisupeni. 2002. Peran Status Kelahiran terhadap Stunting pada Bayi: Sebuah Studi Prospektif, Jurnal Kedokteran Trisakti. Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat: Universitas Indonesia. 23 (3): 73-80.
Lee, P. dan Wu, X. 2015. Review: Modifications of Human Serum Albumin and Their Binding Effect, HHS Public Access. Chicago: University of Chicago. 21 (14): 1862-1865.
Lewit, E.M. 1997. Population-based Growth Stunting, the Future of Children Journal. New Jersey: Princeton University. 7 (2).
Miyamoto, T., Matsushima, F., dan Nakae, T. 1986. Yogurt-like Fermented Bean Milk Prepeared by Lactic Acid Bacteria from Tropical Vegetation, Japan Journal Zootech. Sci. Laboratory of Animal Products Technology: Okayama University. 57 (5): 422-429.
Mustakim, M. 2012. Budidaya Kacang Hijau Secara Intensif. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Picauly. 2013. Analisis Determinan dan Pengaruh Stunting terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah di Kupang dan Sumba Timur, NTT, Jurnal Gizi dan Pangan. Kupang: Universitas Nusa Cendana. 8 (1): 55-62.
Plantenga, M.S.W., Marsh, N.L., Lejeune, M.P.G.M., Diepvans, K., Nieuwenhuizen, A., dan Engelen, M.P.K.J. 2006. Dietary Protein, Metabolism, and Body-weight Regulation: Dose-response Effects, International Journal of Obesity. Netherlands: Maastricht University. 30: 16-23.
Putri, Y.U. 2010. Studi Pembuatan Tepung Biji Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus (L) DC) dengan Metode Penggilingan Basah dan Analisis Sifat Fisiko-kimia serta Karakteristik Fungsionalnya, Skripsi. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor.
Rahino, R.P. 2018. Penanganan Stunting Jadi Prioritas Provinsi Kalbar, Ini Langkah Konkrit yang dilakukan Pemerintah. Http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/18/penanganan-stunting-jadi-prioritas-provinsi-kalbar-ini-langkah-konkrit-yang-dilakukan-pemerintah. Diakses Tanggal 20 Januari 2019.
Riset Kesehatan Dasar. 2018. Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. Pusat Data dan Informasi. ISSN: 2088-270 X.
Rukmana, R. 2000. Kecipir, Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen. Yogyakarta: Kanisius.
Samosir, D.J. 1985. Studi Laboratoris dan Biologis Biji Kecipir sebagai Bahan Makanan, Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Shinya, H. 2010. Mengubah Mikroba dalam Tubuh Kita Menjadi Menguntungkan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Soenardi, T. 2006. Gizi Seimbang untuk Anak dan Balita dalam Hidup Sehat Gizi Seimbang dalam Siklus Kehidupan Manusia. Jakarta: Gramedia.
Suarni dan Widowati, S. 2006. Struktur, Komposisi, dan Nutrisi Jagung. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
Taufiqurrahman, H.H., Julia, M., dan Herman, S. 2009. Defisiensi Vitamin A dan Zinc sebagai Faktor Risiko Terjadinya Stunting pada Balita di Nusa Tenggara Barat, Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Nusa Tenggara Barat: Department of Nutrition, Mataram Health Polytechnic.
Timaeus, I.M. 2012. Stunting and Obesity in Childhood: A Reassessment using Longitudinal Data from South Africa, International Journal of Epidemiology. London: Department of Population Studies. 1-9.
Umeta, M. 2003. Factors Associated with Stunting in Infants Aged 5-11 Mounths in the Dodotasire Districk, Rural Ethiopia, Journal Nutrition. Netherlands: Wageningen University. 133: 1064-1069.
Unicef. 1990. Strategy for Improved Nutrition of Children and Women in Developing Countries. New York.
Unicef. 2013. Improving Child Nutrition the Achievable Imperative for Global Progress. Www.unicef.org/media/files/nutrition_report_2013.pdf. Diakses Tanggal 10 Mei 2019.
Utami, K.D. 2011. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemberian MP-ASI Dini pada Bayi Kurang dari 6 Bulan di Desa Sutopati. Ciputat: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN.
WHO. 2003. Global Strategy for Infant and Young Child. Geneva: World Health Organization.
Winarno, F.G. 1987. Gizi dan Makanan Bagi Bayi Anak Sapihan, Pengadaan dan Pengolahannya. Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Zakaria, Tamrin, A., Sirajuddin, dan Hartono, R. 2012. Penambahan Tepung Daun Kelor pada Menu Makanan Sehari-hari dalam Upaya Penanggulangan Gizi Kurang pada Anak Balita, Media Gizi Pangan. Makassar: Jurusan Gizi Poltekkes Kesehatan Kemenkes.
Ziegler, T.R., Bazargan, N., dan Galloway, J.R. 2000. Glutamine Supplemented Nutrition Support: Saving Nitrogen and Saving Money, Clinical Nutrition. Georgia: University Hospital. 19 (6): 375-377.
BIODATA PENULIS
Nama Lengkap : Deri Agustiawan
Semester : Empat (4)
Prodi : Kimia

 Upaya yang dilakukan pemerintah Kalimantan Barat dalam mengatasi stunting selama ini hanya melakukan peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi lingkungan (Rahino, 2018). Cara tersebut dinilai masih belum efektif karena stunting terjadi akibat kurangnya asupan makanan bergizi seimbang sehingga kebutuhan asupan makanan dapat menjadi solusi untuk mengatasinya. Pemenuhan zat gizi baik gizi makro maupun gizi mikro sangat dibutuhkan untuk menghindari atau memperkecil risiko stunting. Kualitas dan kuantitas MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang baik merupakan salah satu komponen terpenting dalam makanan karena mengandung sumber gizi makro dan mikro yang berperan dalam pertumbuhan linier (Taufiqurrahman et al., 2009). Pemberian makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, kalsium, vitamin A dan zinc dapat memacu tinggi anak (Kusharisupeni, 2002).
MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI (Winarno, 1987). World Health Organization menerapkan standar MP-ASI untuk bayi harus mengandung protein, energi dan nutrisi yang cukup. Makanan tambahan diberikan untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan nutrisi total pada anak dengan jumlah yang didapatkan dari ASI sekaligus menanamkan kebiasaan makan yang baik (WHO, 2003; Utami, 2011). Pemberian MP-ASI yang cukup kualitas dan kuantitasnya penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang sangat pesat pada periode ini, tetapi sangat diperlukan hygiene dalam pemberian MP-ASI tersebut. Sanitasi dan hygiene MP-ASI yang rendah menyebabkan terjadinya kontaminasi mikroba yang dapat meningkatkan risiko atau infeksi lain pada bayi (Winarno, 1987).
Upaya yang dilakukan pemerintah Kalimantan Barat dalam mengatasi stunting selama ini hanya melakukan peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi lingkungan (Rahino, 2018). Cara tersebut dinilai masih belum efektif karena stunting terjadi akibat kurangnya asupan makanan bergizi seimbang sehingga kebutuhan asupan makanan dapat menjadi solusi untuk mengatasinya. Pemenuhan zat gizi baik gizi makro maupun gizi mikro sangat dibutuhkan untuk menghindari atau memperkecil risiko stunting. Kualitas dan kuantitas MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang baik merupakan salah satu komponen terpenting dalam makanan karena mengandung sumber gizi makro dan mikro yang berperan dalam pertumbuhan linier (Taufiqurrahman et al., 2009). Pemberian makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, kalsium, vitamin A dan zinc dapat memacu tinggi anak (Kusharisupeni, 2002).
MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI (Winarno, 1987). World Health Organization menerapkan standar MP-ASI untuk bayi harus mengandung protein, energi dan nutrisi yang cukup. Makanan tambahan diberikan untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan nutrisi total pada anak dengan jumlah yang didapatkan dari ASI sekaligus menanamkan kebiasaan makan yang baik (WHO, 2003; Utami, 2011). Pemberian MP-ASI yang cukup kualitas dan kuantitasnya penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang sangat pesat pada periode ini, tetapi sangat diperlukan hygiene dalam pemberian MP-ASI tersebut. Sanitasi dan hygiene MP-ASI yang rendah menyebabkan terjadinya kontaminasi mikroba yang dapat meningkatkan risiko atau infeksi lain pada bayi (Winarno, 1987).
Tabel 1. Komposisi Gizi dalam 100 Gram MP-ASI Bubur Instan
| Zat Gizi | Satuan | Kadar |
| Energi | kkal | 400-440 |
| Protein | g | 15-22 |
| Lemak | g | 10-15 |
| Gula | g | Maksimum 30 |
| Serat | g | Maksimum 5 |
| Vitamin A | mcg | 250-350 |
| Besi | mg | 5-8 |
| Kalsium | mg | 200-400 |
| Seng | mg | 2,5-4,0 |
| Air | g | Maksimal 4 |
(Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2007)
Pemberian MP-ASI yang salah akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan terjadinya penyimpangan berat badan yang cenderung menurun (Soenardi, 2006). Studi multisenter tentang MP-ASI menunjukkan bahwa MP-ASI yang diberikan pada anak balita masih dibawah AKG (Angka Kecukupan Gizi), terutama masalah rendahnya mikronutrien pada MP-ASI tradisional yang hanya memenuhi 20% AKG (Dini et al., 2007). Pemberian MP-ASI sangat dianjurkan untuk penderita KEP (Kekurangan Energi Protein), terlebih bayi berusia diatas enam bulan dengan harapan MP-ASI ini mampu memenuhi kebutuhan gizi dan mampu memperkecil kekurangan zat gizi (Ziegler et al., 2000). Oleh karena itu, dibutuhkan solusi sumber bahan untuk MP-ASI yang berpotensi di Kalimantan Barat, salah satunya kecipir (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.). Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) merupakan tanaman yang sangat melimpah keberadaannya di Kalimantan Barat dan mudah ditemukan pada daerah yang beriklim tropis dan subtropis namun pemanfaatannya yang masih kurang. Tanaman kecipir tumbuh sepanjang tahun di Indonesia dengan hasil panen tahunan sebanyak 2.380 kg/ha hingga 4.500 kg/ha (Samosir, 1985; Miyamoto et al., 1986; Rukmana, 2000). Apabila kecipir tidak langsung diolah maka akan mudah teroksidasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan visual berupa warna hitam pada sisi buah kecipir, lunak, berjamur dan akhirnya menjadi busuk sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kehilangan hasil panen dan penurunan harga yang tajam saat terjadi panen raya di daerah sentra produksi (Apriliyanti, 2010). Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu diversifikasi pangan berupa fortifikasi dalam bentuk olahan tepung agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
Gambar 2. Polong Muda dan Polong Tua (Handayani, 2013)
Pemanfaatan daun dan biji kecipir dilakukan dengan mengubah bentuk kecipir menjadi tepung. Pembuatan tepung biji kecipir mengacu pada penelitian Yelita Utami Putri (2010) dilakukan dengan cara biji kecipir direndam dalam air bersih pada suhu ruang selama 18 jam dan dicuci setiap 6 jam. Perendaman berfungsi untuk membersihkan biji kecipir dari kotoran. Biji kemudian direbus selama 120 menit. Pemanasan berfungsi untuk melunakkan biji kecipir. Setelah direbus, biji kecipir ditiriskan dan dilakukan pengupasan kulit luarnya. Penirisan berguna untuk memisahkan antara biji kecipir dengan air serta pengupasan berguna untuk memisahkan biji kecipir dengan kulit luarnya. Biji kecipir ini kemudian digiling dengan penambahan akuades (biji kecipir: akuades = 1:3). Suspensi ini diatur pH dengan penambahan NaOH hingga pH 10 dan diekstrak kembali selama 60 menit. Kemudian disaring untuk memisahkan suspensi dengan hancuran biji kecipir yang kasar. Bagian yang lolos saringan diatur pHnya dengan penambahan HCl hingga pH isoelektrik. Kemudian dilakukan pengendapan sampai terbentuk dua lapisan yaitu lapisan endapan biji kecipir dan lapisan air yang jernih. Tahap selanjutnya adalah pemisahan endapan dari lapisan air sehingga diperoleh tepung biji kecipir basah. Tepung basah ini kemudian dikeringkan dengan pengeringan sinar matahari. Setelah kering, tepung yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran ini digiling kembali dengan blender kering. Kemudian diayak dengan ayakan 60 mesh. Tepung biji kecipir ini kemudian disimpan pada tempat tertutup sebelum digunakan. Tepung biji kecipir yang dibuat memiliki ukuran partikel yang halus dan kemampatan yang sesuai dengan produk tepung-tepungan. Tabel 2. Komposisi Kimiawi Bagian-Bagian Tanaman Kecipir (g/100g)| Kandungan Kimiawi | Daun | Biji |
| Energi | 0,20 (x) g | 1,61-1,89 g |
| Protein | 5,00-7,60 g | 29,80-39,0 g |
| Lemak | 0,50-2,50 g | 15,0-20,40 g |
| Karbohidrat | 3,00-8,50 g | 23,90-420 g |
| Serat | 3,00-4,20 g | 3,70-16,10 g |
| Kalium | 80-436 mg | 1.110-1.800 mg |
| Fosfor | 52-98 mg | 200-610 mg |
| Besi | 2,00-6,20 mg | 2,00-18,00 mg |
| Seng | 1,40 mg | 3,10-5 mg |
| Vitamin A | 5.240-20.800 IU | – |

[learn_press_profile]
Tag:daun dan biji, informasi, kecipir, mahasiswa, pendek, penelitian, rektor, stunting, tepung, untan